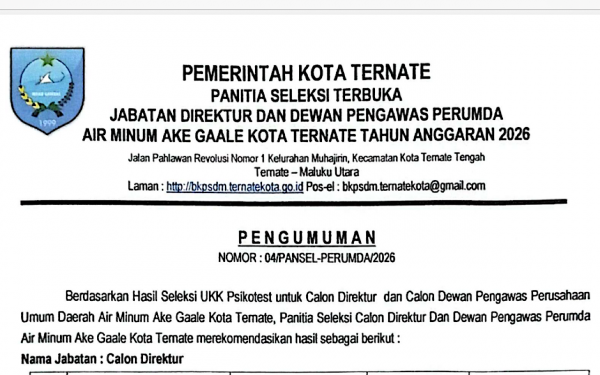MENJELANG Pemilu kita sering mendengar kata populisme. Saya membaca bahwa kata populisme berasal dari kata populum yang berarti rakyat, muncul di abad ke-19 dan mau mengungkapkan persepsi “rakyat yang murni” berhadapan dengan “elite yang korup” (Suseno 2021, 6). Lebih jelas, dalam kamus sosiologi, populisme diartikan sebagai “suatu bentuk khas retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat, memandang kelompok elit yang dominan sebagai korup, dan bahwa sasaran-sasaran politik akan dicapai paling baik melalui cara hubungan langsung antara pemerintah dan rakyat, tanpa perantara lembaga-lembaga politik yang ada” (Abercrombie et. Al., 1998: dalam Muhtadi, 2019).
Jadi, konteks populisme hari ini adalah suatu gerakan massa rakyat sebagai akibat dari akumulasi kemarahan dan kemuakan atas perpolitikan formal yang hanya dikuasi oleh segelintir elite, serta dilakukan hanya demi kepentingan elite yang korup. Populisme merupakan sikap etis untuk berani mengatakan sudah “cukup” dan menuntut elite politik untuk melakukan perbaikan, perubahan bagi kemajuan bersama.
Dalam literatur politik Barat, populisme mulai dikenal pasca berakhirnya Perang Dunia I. Amerika Latin dengan Benito Mussolini (1883-1945) yang khas populis. Ia mengambil alih kekuasaan Italia tahun 1922 melalui slogan “make Italia grate again”, slogan ini membangkitkan memori rakyat Italia akan kejayaan masa lampau Bangsa Romawi yang berjaya lebih dari seribu tahun. Begitu juga Jerman ketika mengalami krisis pasca Perang Dunia I, demokrasi lahir menggantikan pemerintahan monarki.
Adolf Hitler yang merasa bangsanya dihina, direndahkan dan dituduh penyebab perang Dunia I tidak mengakui demokrasi karena merasa dipaksakan oleh sekutu Barat kepada bangsa Jerman yang kalah perang. Janjinya untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Jerman dan menghancurkan sekutu Barat menghantarkan Adolf Hitler sebagai pemimpin (der Fuhrer) tahun 1933. Di Amerika Latin muncul gerakan populis baru yang bernama “peronistas” pasca Perang Dunia II dan kemudian melahirkan Juan Domingo Peron sebagai presiden yang terpilih sebanyak tiga kali (1946-1955). Juan dipilih oleh gerakan “peronistas” yakni dukungan dari pihak tertindas; rakyat pekerja di sektor pertanian dan industri.
Crista Deiwiks dalam bukunya Muhtadi (2019), memetakan krisis dalam tiga bentuk. Pertama, kondisi krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pertumbuhan, dampak globalisasi, eksploitasi sumber daya alam. Kedua, populisme merupakan kritik tajam atas kegagalan representative democracy. Ketiga, kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat ditambah janji-janji demokrasi untuk yang kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin populis sebagai retorika politik. Dengan demikian titik tolak populisme menjadi terang benderang. Populisme mendapat persemaian yang subur ketika ketidakadilan dan krisis dirasakan masyarakat.
Di Indonesia, jalan panjang resim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto berakhir dengan penyematan sebagai sebagai resim terlama yang memimpin Republik ini, yakni kurang lebih 32 tahun. Rakyat Indonesia melalui mahasiswa dan pemuda/I, melalui ketajaman visi dan pergerakan yang Revolusioner berhasil menumbangkan resim Soeharto yang otoriter dan korup. Salah satu semangat Reformasi pasca jatuhnya Presiden Soeharto adalah memperpendek masa kekuasaan. Sebab kekuasaan yang lama akan cenderung menciptakan pemimpin dan rezim yang otoriter, diktator dan korup seperti dalam dalil Lord Acton “power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”.
Semangat inilah yang pada akhirnya melahirkan satu lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memperkuat peran, fungsi dan strukturnya. KPU mempunyai tugas yang mulia, secara teknis berfungsi untuk menyelenggarakan pemilu dan secara etis berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat dalam iklim demokrasi. Penguatan peran, fungsi dan struktur inilah yang membedakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lahir pasca Orde Baru tumbang dan Lambaga Pemilihan Umum (LPU) yang didirikan presiden Soeharto ketika tahun 1970.
Sebagai lembaga negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu. Maka, landasan KPU dalam menyelengarakan Pemilu tahun 2024 adalah Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024.
Indonesia pada Pemilu pertama tahun 1999, yang saat itu menerapkan demokrasi liberal tidak tercium bau-bau munculnya populisme agama. Parpol-parpol yang berasaskan Islam kalah dari parpol berasaskan Pancasila. Kemenangan parpol Nasionalis atas Parpol Islam lebih dipertajam dengan gagalnya parpol Islam mengusung Paslon Capres-Cawapres hingga dianggap hanya pelengkap “bunga-bunga demokrasi” saja.
Baru dibawah kepemimpinan Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo Istilah Populisme agama mencuat diikuti dengan sejumlah aksi massa kalangan “pembela Islam” pada akhir tahun 2016-2017. Gelombang aksi “bela Islam” yang begitu kental dengan massa yang besar diikuti dengan narasi kebencian terhadap Ahok digelorakan lewat aksi massa yang berjilid-jilid itu. Kasi bela Islam 14 Oktober 2016, 28 Oktober 2016, 4 November 2016, 2 Desembaer 2016, 11 Februari 2017, 21 februari 2017, 31 Maret 2017, dan 5 Mei 2017.
Buntut dari aksi massa ini dikarenakan Ahok dianggap menghina Islam pada saat itu. Gerakan ini tidak bebas kepentingan melainkan sebagai upaya menghalangi Ahok terpilih menjadi Gubernur. Puncaknya ketika momentum Pilkada 2017, Anis Baswedan-Sandiaga Uno keluar bak pahlawan bagi kalangan Islam fundamental. Kemenangan Anis-Sandi adalah kemenangan kelompok massa “pembela Islam” dengan strategi populisme Politik Islam.
Berbeda tetap Berbeda
Di Prancis tahun 2018, secara mendadak meledak sebuah gerakan yang bernama yellow vests movement. Dalam gerakan itu, sebanyak 30 % rakyat kelas bawah mendadak mengatakan sudah cukup masa kepemimpinan Presiden Macron, cepat turun dari jabatan Presiden! Gerakan ini lahir dari kondisi faktual yang dirasakan masyarakat Perancis, bahwa perpolitikan dan orientasi kesejahteraan hanya di Paris saja sehingga “kami” dilupakan. Meskipun akhirnya redup, setidaknya kemarahan rakyat melalui aksi massa tersebut menyisahkan kerusakan sepanjang jalan Paris.
Di tengah perkembangan politik, kebijakan pemerintah (public policy) yang timpang, orientasi pembangunan yang tidak mengakomodir kepentingan rakyat, maka pada akhirnya yang tertindas dan yang teralineasi akan menemukan kesamaan identitasnya. Maka dalam perasaan yang bergejolak seperti “kami dilupakan” kami dimanfaatkan, sekarang kami tak mau lagi, kami tidak menerima lagi, kami dibodohi, kami dibohongi, semua kekejian ini dilakukan oleh “mereka”.
Kata “kita” diganti “kami” selanjutnya dipisahkan dengan “mereka” bermuara pada kesimpulan “kami bukan “mereka”. Pada titik ini populisme tumbuh dengan kesan sebagai suatu gerakan progresif ketika menyatakan diri secara berani untuk memperjuangkan sesuatu yang dibela dalam satu gelombang besar dan kokoh. Populisme saya sebut sebagai “sang pembela”. Romo Magnis menyebutnya sebagai identity obsession. Persolan-persoalan diatas menjadi bahan bakar gerakan politik populisme baik dikancah nasional maupun dipakai dalam Pemilu di daerah.
Isu dan gerakan populisme menjadi lebih tajam dan progresif disaat komposisi etnik, kesukuan dan agama di suatu daerah/wilayah mengalami ketimpangan. Mulai dari timpangnya komposisi lembaga Triaspolitika (eksekutif, legislatif, yudikatif), orientasi pembangunan yang sentralistik, konsolidasi kebudayaan yang sentralistik, serta distribusi sumber daya manusia (SDA) yang berdasarkan privilege tertentu dst. Semua wajah ini tersketsa dengan jelas di beberapa daerah tidak terkecuali kabupaten/kota di rpovinsi Maluku Utara. Seperti “bom waktu” tinggal menunggu momentum dan populisme “kami” akan keluar sebagai pemenang.
Senjata “Mereka” sudah tidak mempan
Jalan populisme sengaja dipilih untuk menegaskan keberpihakannya kepada golongan masyarakat tertentu. Paling tidak sejak masa kampanye narasi-narasi keberpihakan itu mulai disuaraka hingga terpilih dan dalam menjalankan kekuasanpun narasi dan kebijakan populis genjar dipromosikan. Tidak mengherankan apabila paslon tertentu berkampanye di tempat basis massanya (kedekatan primordial) dan kemudian memberikan janji politik dengan narasi populisme.
Tidak terbatas pada basis massa saja, cerdiknya para politisi mampu melakukan improvisasi dilapangan ketika berada di luar basis massa dengan melihat realitas sosial, ekonomi dan kondisi politik di tempat itu. Isu-isu seputar realitas sosial tersebut yang kemudian dipakai dan dimanfaatkan untuk disusupi narasi populis sehingga massa tergerak dan memilih paslon tersebut. Paul Taggart menganalogikan populisme seperti (hewan) bunglon yang bisa berubah-ubah warna kulitnya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya (Muhtadi 2019, 2)
Mereka dipilih bukan karena benar-benar bisa merealisasikan janji akan kemajuan ekonomi, kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, bodoh amat dengan infrakstruktur jalan dan jembatan yang akan dibangun (untuk “kami”) atau karena lebih mempunya kapasitas dan keunggulan program melainkan semacam keegoisan agar kelompok “mereka” tetap di pucuk pimpinan. Asalkan jangan “kami” itu kalimat yang sudah biasa “kami” dengar.
Perilaku memilih merupakan satu hal yang sangat kompleks. Faktor primordial menjadi faktor utama dan bisa jadi mengikat kelompok tertentu. Paslon dengan identitas primordial yang mayoritas, maka akan dengan mudah mengkonsolidasi gerakan politik dan akan mendulang bayak suarah. Sebaliknya strategi Paslon yang lemah dari sisi identitas primordial akan memakai cara apapun untuk membalikan kemenangan berpihak padanya. Salah satunya dengan “Money Politics”. Politik bayar suara menjadi senjata ampuh bagi “mereka” yang secara kuantitas dan kualitas adalah minoritas. Strategi “mereka” sampai sekarang terbukti berhasil, tapi tidak pada Pemilu tahun 2024 nanti. Kita buktikan nanti!!!
“Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksadirinya dengan berbagai-bagai duka”
(1 Timotius 6:10)
“hoye dika manga tiwi, uha manyawa”
(anonym)
Golput?
Istilah golput disingkat dari “golongan putih”, menurut Wikipedia diciptakan tahun 1971 oleh Imam Waluyo bagi mereka yang tidak mau memilih. Dipkai istilah “putih” karena gerakan ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar parpol peserta pemilu kalau tidak menyetujui pembatasan pembentukan partai-partai politik oleh pemerintah Orde Baru (Suseno 2021, 15).
Saya akan berangkat dari sebuah sikap sebagai anak bangsa untuk patuh pada Undang-Undang. Namun, sepanjang yang diketahui tidak ada satupun ayat di dalam Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan warga negara untuk harus menggunakan hak pilihnya. Disinilah titik permenungan bagaimana kita memaknai yang tidak ditulis itu secara bijak dan konsekuen. Maka, ikut memilih dalam Pemilu bukan merupakan wajib Hukum, melainkan wajib Moral sebagai anak bangsa yang peduli akan perbaikan proses pelembagaan demokrasi.
Setiap kali ada Pemilihan Umum, beberapa dari kita sering kebingungan memilih Paslon yang sesuai dengan preferensi pribadi. Dalam kebingungan itu saya sebut “kelabilan mental”, maka akan timbul sikap untuki abstain dalam Pemilu. Iklim demokrasi tidak menjamin yang sempurna untuk dipilih karena memang tidak ada Paslon yang sempurna, melainkan sebisa mungkin memastikan yang terburuk tidak terpilih. Tidak ada absulitisme dalam demokrasi yang ada hanya probabilitas, maka pilihlah Paslon yang memiliki probabilitas paling tinggi tercapainya visi rakyat adil dan makmur (amanat UUD 1945).
Hotu!!!
Yee…
*Oleh: Jeffrendsky Ngama Kolong
(red)